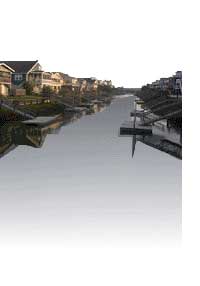Kesehatan
Diswastakan...
Oleh Ashari Cahyo Edi
Seperempat jam lalu, saya melihat berita di televisi. Seorang pasien miskin di ditolak berobat di rumah sakit
milik Pemda di Ponorogo. Sejumlah analis di koran mengatakan: ”Rumah sakit kehilangan moral!” (Mahlil Ruby, Kompas,
2005). Situs Up Link, salah satu NGO yang bergerak di sektor kaum miskin kota, suatu waktu mengupas privatisasi di sejumlah
rumah sakit pemerintah secara kritis. Berikut coretan saya yang serba terbatas. Sitasi masih belum lengkap dan akan saya lengkapi
di lain waktu. Jadi tanpa bermaksud tidak etis. Pokok bahasan saya seputar desentralisasi kesehatan dan dampaknya.
Yang pertama, menyangkut perubahan kewenangan. Merujuk regulasi, banyak kewenangan dan tanggung jawab melimpah dari
pusat ke daerah. UU 32/2004 Pasal 1 ayat 5 mengatakan, ”Otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ayat 6 melanjutkan, ”Daerah otonom, selanjutnya
disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.”
Mengenai pembagian urusan, pasal 3 undang-undang yang mengganti UU 22/1999 ini menyebut bahwa urusan pemerintahan yang menjadi
urusan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
Sebagai daerah otonom, pasal 11 menggariskan
bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan pilihan. Urusan yang wajib
dilaksanakan dengan pedoman tandar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk bidang kesehatan, terkait dengan tugas
dan peran kabupaten/kota, diatur dalam paal 14 huruf e. Urusan wajib tesebut mencapai 14 urusan, termasuk di dalamnya bidang
kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten, dan pelayanan dasar lainya serta peran yang diamanatkan
oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai penanganan pelayanan kesehatan, Pasal 22 huruf f melanjutkan bahwa pemerintah
daerah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan secara lebih luas, ”mengembangkan sistem jaminan sosial (huruf
h)”.
Selain kewajiban, pasal 21 UU ini mengatur
hak-hak pemda antara lain: (a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; (c) mengelola aparatur daerah; (d) mengelola
kekayaan; (e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah; (f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam dan
sumber daya lainnya di daerah; (g) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; (h) mendapatkan hak lainnya yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban, berikut otonomi yang dimiliki secara preskriptif akan memberi ruang
yang besar agar di daerah muncul berbagai inovasi dan inisiatif untuk demokrasi lokal dan daerah sejahtera.
Regulasi
lainnya yang turut mengatur peran dan kedudukan aparatur daerah dalam pelaksanaan desentralisasi kesehatan adalah Pemerintah
Nomor 8 2003. perubahan signifikan dari regulasi sebelmnya yakni dipisahkannya dinas dari lembaga teknis daerah dalam
hal ini rumah sakit daerah. Keduanya setara di hadapan kepala daerah. Baik kepala dinas kesehatan maupun direktur rumah sakit
bertanggung jawab kepaa daerah. Ini berbeda dengan regulasi sebelumnya, di mana kepala dinas mensubordinasi lembaga teknis
seperti RSUD.
Selanjutnya dalam regulasi tingkat menteri yakni SE Menkes No. 1107/E/VII/2000 dirinci kewenangan kabupaten/kota
sebagai daerah otonom. Tabel 1 memuat kewenangan desentralisasi daerahKabupaten/Kota.
Dari SK
Menkes tersebut daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan krusial dalam bidang kesehatan. Kegiatannya merentang mulai dari
pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan daerah, perencanaan pembangunan kesehatan wilayah kab/kota, perizinan pelayanan
kesehatan, pengembangan pembiayaan kesehatan, penyelenggaraan promosi kesehatan, bimbingan dan pengendalian upaya/sarana kesehatan
lingkungan skala kab/kota, hingga perizinan kesehatan.
Peran-peran
tersebut dikerangkai dengan road map pembangunan kesehatan dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Melalui
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 004/Menkes/Sk/I/2003, diberikan satu cetak biru Kebijakan dan Strategi
Desentralisasi Bidang Kesehatan. Esensi desentralisasi dari regulasi tersebut tampak dari tujuan desentralisasi di bidang
kesehatan yakni mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan
cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas kesehatan masyarakat
miskin. Daerah diidealkan memprakarsai inovasi dalam hal pembangunan kesejahteraan daerah. Tarikannya adalah tanggung jawab
pemerintah daerah sebagai bagian dari negara untuk menyediakan public goods (pelayanan
kesehatan bagi orang miskin, promosi kesehatan, pencegahan penyakit). Semuanya itu bersifat mendasar dan membutuhkan pelembagaan
(kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan mekanisme pelayanan) yang baik. Kelembagaan tersebut juga diimbangi oleh perubahan-perubahan
secara secara bertahap dari pemerintah dalam hal nilai, perilaku, perspektif dalam relasi dengan masyarakat. Perubahan pada
sisi pemerintah, mengikuti preskripsi yang digariskan kebijakan, penting untuk mengimbangi menggeliatnya semangat partisipasi
warga dalam kebijakan yang terkait langsung dengan kehidupannya.
Karena itu, dalam kebijakan dan strategi
desentralisasi arah yang dituju dari regulasi dan desain yang memberi kerangka an arah bagi pembangunan kesehatan dalam desentralisasi
kesehatan, diharapkan tidak justru mempersulit ketersediaan akses bagi rakyat miskin. Dalam perspektif keberpihakan dan prioritas
program, desentralisasi kesehatan secara spesifik harus diarahkan pada kebijakan dan program pembangunan serta dilengkapi
dengan perencanaanan dan penganggaran di daerah yang mengutamakan akses pelayanan kesehatan bagi orang miskin dan peletakaan
kelembagaan jaminan sosial pemeliharaan kesehatan.
Dalam kebijakan dan strategi tersebut dirumuskan
langkah strategis upaya perlindungan kesehatan dan sub-sistem pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk miskin, kelompok rentan
dan daerah miskin, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah (matching grant). Aspek pembiayaan kesehatan
menjadi penting di tengah besarnya tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk menjamin akses masyarakat miskin atas hak
dasar.
Munculnya
raperda retribusi puskesmas yang kasat mata berakibat naiknya biaya berobat dengan demikian dipandang masyarakat tidak senafas
dengan preskripsi desentraliasi di atas. Upaya “...memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk
kepentingan daerah...”, disalahartikan dengan meningkatkan retribusi. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
di puskesmas juga tampak semata-mata mengedepankan pemenuhan aspek-aspek ekonomis. Sebaliknya, tidak advokatif terhadap peningkatan
belanja sosial (kesehatan), dan rentan membatasi akses masyarakat miskin ketika tarif naik.
***
Kedua, advokasi juga tidak lepas dari konteks keprihatinan atas semakin lepasnya tanggung
jawab negara dan merasuknya mode tata kelola pasar dalam sektor kesehatan. Era otonomi daerah diwarnai adanya kecenderungan swastanisasi
dan privatisasi pelayanan yang dulu dipayungi negara (public sector). Salah satu
gejala yang gamblang adalah maraknya perubahan status rumah sakit dari publik
ke swasta.
Hal ini bisa dirunut dari pandangan yang sesat mengenai
sektor publik. Di masa lalu, pelayanan publik yang diberikan oleh negara bisa dipandang mendekati sekadar suatu benevolency dari negara. Berbeda dengan kebanyakan negara demokrasi yang sudah maju, di mana pelayanan publik
sebagian besar didanai oleh pajak, pelayanan publik dan juga pembangunan lebih banyak didanai sepihak oleh negara. Puncaknya,
sumber daya nomplok hasil oil boom memberi keleluasaan yang besar bagi Orde Baru
untuk melakukan ekspansi dalam pelayanan publik. Keberlimpahan tersebut membawa fenomena paradox
of plenty, yakni suatu keadaan yang ditandai melimpahnya sumber daya yang besar untuk keleluasaan pelayanan publik dan pembangunan,
namun negara mendistribusikan secara deskriminatif—sering sebagai politik carrots
and sticks sehingga tidak membawa manfaat bagi seluruh rakyat. Hanya RT, kampung, kelompok, atau suku tertentu yang mendapatkan
manfaatnya. Rakyat dalam relasinya dengan negara dalam pelayanan publik cenderung sebatas klien atau konstituen. Parahnya, konstituen atau klien dipersempit terutama bagi pendukung rezim.
Saat kapasitas finansial negara merosot, ”paham pelayan publik lama”
ini juga berimbas. Karena dipandang sebagai benevolensi, pelayanan juga ikut mengalami kemunduran karena komitmen pembiayaan
tidak sepenuhnya dalam kerangka pemenuhan kewajiban negara. Hal tersebut beriringan dengan menguatnya paham baru new public menagament dengan avant garde pendekatan Osbornian melalui reinventing government-nya. Birokrasi dari pusat hingga level daerah pun secara latah
mengumbar jargon swastanisasi birokrasi atau mewirausahakan
birokrasi. Pelayanan publik dipandang sebagai konsumsi, menghabiskan uang, dan tidak berkontribusi positif bagi anggaran
pemerintah. Terlebih, desentralisasi ditandai oleh kecilnya APBD terutama daerah yang miskin sumber daya alam. Setali tiga
uang dengan enggannya birokrasi untuk memotong kepentingannya sehingga alokasi belanja langsung daerah bisa semaksimal mungkin
untuk pelayanan publik dan pembangunan.
Shifting atau pergeseran dalam pilihan paradigma pengelolaan pelayanan publik ini mempengaruhi karakter
delivery, status penerima manfaat, penangung beban pembiayaan, yang selanjutnya
menegaskan peran dan posisi baik negara, pasar, dan masyarakat. Oleh managerialist
epistemics, sektor publik kerap diserang karena sejumlah hal. Pertama, peran pengelola sektor publik membuat ukuran pemerintah gemuk, mengonsumsi terlalu banyak
sumber daya, bekerja pada at all cost. Kedua, lingkup peran yang terlalu luas dan dominan di hampir semua ranah sehingga
peran swasta tak berkembang. Sementara, sektor swasta dengan ”principal agent”
yang jelas, kualitas dan performa dengan serendah-rendahnya cost, justru tidak
diuntungkan oleh regulasi. Ketiga, birokrasi sebagai lembaga menjadi tidak populer, dipandang sebagai pelestari inefisiensi
dan mediocrity atau incrementalism.
Trend baru tersebut membawa dua arus yang saling: (1) menjauh dari apapun mode kepengurusan bersama yang ”birokratis”; (2) diadopsinya preskripsi nilai, managemen, dan mode/operasionalisasi market based
(economic rationalism)—lihat misal Dryzek (2000)—dalam pegelolaan sektor publik.
Pihak yang pecaya pasar menolak adanya intervensi. Beberapa argumen
yang diserang terkait dengan hadirnya sektor publik sebagai pengelola tunggal atas barang dan jasa publik (public goods).
Pertama, menolak pandangan ”there won’t be enough suppliers
to permit competition”. Implikasi dari klaim ini bahwa hanya ada satu tangan penyedia yang sungguh memenuhi syarat
untuk memimpin monopoli atau oligopoli. Sebuah monopoli publik yang permanen dipandang lebih baik daripada monopoli temporer
swasta. Juga pandangan bahwa civil servant, PNS lebih memliki sense altruistik,
atau tercerahkan di banding rata-rata pengusaha. Kedua, menolak ”many public (goods) services are natural
monopolies, so they should be operated by public sector”. Mereka mempertanyakan apakah pelayanan tersebut sungguh
monopoli natural, dan apakah sektor publik menjadi jalan yang paling baik. Mereka mencurigai hal itu tak lain hanyalah trik
birokrasi untuk memotong jalur masuk provider swasta. Kemudian, meski ada konsensus politik bahwa penyediaan barang
harus dimonopoli, harus dicurigai klaim bahwa sektor publik merupakan yang terbaik. Sebaliknya, sektor swasta atau sistem
yang mengizinkan adanya persaingan akan menghasilkan jaminan dan perlindungan pelayanan yang lebih rendah harganya dengan
kualitas yang juga bersaing. Ketiga, ”the service must be provided by the state to ensure that the poor will have
access to it”. Ini menjadi argumen dipercayanya negara sebagai penyedia, membuat barang/jasa publik tersedia bagi
siapapun, tanpa charges bagi pengguna, seing pada tingkat subsidi harga yang tinggi.
Namun hal ini dipandang justru berbahaya bagi publik karena menumbuhkan rendahnya sensitivitas pada manajemen cost dan karyawan, berlanjutnya terus-menerus terjebak dalam rute dan sikap toleransi terhadap pembayaran di bawah
skala pasar dan inefisiensi dalam kinerja. Sistem subsidi justru merugikan publik sejatinya, sebab tidak responsif terhadap
perubahan permintaan atas pelayaanan. Orang miskin menjadui rentan karena mereka bergantung pada harga subsidi publik, di
mana mereka sendiri adalah pembayar pajak. Kemudian kelemahan aturan main bisa menumbuhkan praktik free riders. Keempat,
”public services should be organized for service not for profit.” Hal ini dipandang purely emosional dan ideologis
ketimbang praktikal dan faktual. Karena memperoleh untung adalah naluri manusia. Hal itu adalah insentif yang menumbuhkan
progress bagi orang.
Kasus perubahan rumah sakit menjadi perseroan terbatas agaknya menjadi contoh
menarik baik terkait perubahan mode tata kelola berikut dampaknya bagi “jati diri” kepublikan sektor kesehatan.
Privatisasi diidentikkan dengan
kemandirian rumah sakit dalam terutama manajemen, keuangan, dan fungsinya terkait tanggung jawab pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Dengan menjadi PT maka RSUD adalah badan bisnis yang melayani dengan dasar kontrak penjual dan pembeli layanan.
Di berbagai negara pelepasan RSUD ke swasta lazim disebut hospital corporatization. (1) Suatu tahap perubahan dari bentuk
lembaga pemerintah dari rumah sakit sebagai unit birokrasi pemerintah; (2) rumah sakit sebagai unit otonomi; (3) rumah sakit
sebagai unit korporasi; dan (4) rumah sakit yang diswastanisasikan.
Korporatisasi ini mempunyai prinsip mempertahankan kepemilikan pemerintah tetapi
mengurangi biaya rumah sakit dengan cara: (1) memberikan wewenang untuk meningkatkan penerimaan dari pasien; (2) mengubah struktur insentif di rumah sakit. Proses corporatization mengarah menjadi suatu lembaga usaha dan adanya pemisahan antara
sebagai pembayar dengan pemberi pelayanan. Konsekuensnya, bisa saja terjadi hubungan kontraktual antara pemerintah dengan
RS—berbeda dengan dahulu saat pemerntah mampu menggerakkan RS untuk misi politik tertentu. Pemerintah misalnya, kini
mulai melakukan subsidi bukan lewat RS langsung tapi melalui askes kepada individu. Dengan begitu, maka RS relatif bebas bergerak.
Korporatisasi rumah sakit di era otonomi daerah mulanya membawa ketegangan antara
dinas kesehatan dengan rumah sakit daerah. Sebelumnya, direktur rumah sakit bertanggung jawab kepada kepala dinas. Namun kini,
bupati/walikota secara langsung menerima pertanggung jawaban dari direktur RSD. Dinas daerah kehilangan kendali (peran rowing) dalam melalui RSUD. Secara umum, perubahan ini oleh pemerintah daerah dipandang
sebagai upaya untuk mendorong rumah sakit profesional. Kendati ada pergesekan antara dinas dengan rumah sakit, namun visi
besar tersebut diutamakan: pengelolaan berbasis pasar.
Sebagai terobosan cara, tujuan akhir yakni sampainya pelayanan ke tangan beneficiaries
justru dipertaruhkan. Ada sesat pikir dalam tubuh birokrasi—tertama terkait dengan budaya kerja dan kapasitas personil—di
mana mode baru tersebut justru disesat-maknai sebagai berkurangnya atau menjadi minimnya tanggung jawab pemerintah (yang tak
lain, sekadar mengingatkan, aktor negara sub nasional). Tidak terintegrasinya pelayanan hak dasar dengan visi dan misi filosofis
pelayanan publik menyebabkan ”tujuan menghalalkan cara”. Alhasil, pergeseran ini di banyak negara dunia ketiga
menimbulkan ancaman bagi akses pelayanan masyarakat.
Dengan trend kebijakan makro nasional, perencanaan kebijakan dan juga demi peran
penunjang penyelenggaraan pemerintahan, banyak daerah lantas mengubah dinas teknis menjadi perseroan terbatas (PT) dengan
kepemilikan pemda. Itu dilakukan demi mengejar efisiensi, memangkas pemborosan (kinerja tak efisien maupun korupsi). Namun
karena bentuknya PT, banyak kritikan dari banyak pihak bahwa pemda ingin lepas tangan dari tanggung jawabnya dan berupaya
menambah pundi-pundi keuangannya sendiri.
Hal ini juga terkait problem dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, yang
justru didominasi oleh belanja tidak langsung (untuk gaji dan operasional birokrasi) dan sedikit untuk belanja langsung ke
pembangunan dan pelayanan publik. Kritikan juga mengarah bahwa pemerintah daerah yang telah semakin memposisikan masyarakat
sebagai customer. Transaksinya dengan begitu adalah ekonomis dan bukan politis.
Yang tidak diperhatikan, pilihan untuk memprivatisasi
jika tanpa disertai transparansi, masih memungkinkan vested interest birokrasi
bermain. Seperti fenomena ISO-nisasi. Di satu sisi, adanya ISO memberikan garansi kualitas layanan, namun tetap akan membebani. Pelayanan
yang berkualitas membutuhkan pendanaan yang mencukupi. Dengan tuntutan kaidah managemen, unit
cost based for pricing the services, akan membuat tarif layanan naik. Jika bukan pemda, maka masyarakatlah yang menanggung.
Kekhawatiran terkait dengan gejala peralihan menuju mode pasar adalah soal
bagaimana menjamin akses atas layanan dan pelembagaan pertanggungjawaban. Selama ini, bahkan ketika lembaga RSUD beralih ke
PT adalah, delivery system tetap belum dilekati dengan kontrol publik. Di mana
mengadu, apakah ada jaminan tindak lanjut pengaduan berikut adanya perbaikan pasca pengaduan, belum ada. Malahan, status rumah
sakit daerah sebagai lembaga birokratik yang berubah menjadi PT telah menghilangkan jalinan akuntabilitas politik. Beranjak
dari berbagai uraian tersebut, advokasi agar masyarakat mampu dan terlibat untuk turut memutuskan berbagai pilihan kebijakan
dalam pelayanan kesehatan di daerah menjadi sentral.
Baik pergeseran kewenangan maupun mode tata kelola sektor kesehatan yang mengarah
ke pasar merupakan konteks advokasi yang dilakukan oleh masyarakat. Desentralisasi dengan kewengan baru menuntut pengutamaan
kinerja pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara dalam sektor kesehatan, sementara peralihan ke swasta perlu diawasi
dan dikontrol.
Owen Hughes, Owen Hughes, Introduction
to Public Administration and Management, Macmillan Press, NY, 1993.
Uraian mengenai perbedaan pengelolaan dari sudut negara (administrative rationalism), pasar (economic rationalism), dan demokrasi
(model representatif, yang ia sebut democratic pargmatism) dipahami dari uraian
John S. Dryzek kendati sektor yang diamati adalah lingkungan. Lihat John S. Dryzek, The
Politics of the Earth: Environmental Discourses, Oxford
University Press, Oxford
1997.
Saya peras dari ulasan M. Peter Mchpherson, ”The Promise of Privatization”
dalam Steve H. Hanke (editor), Privatization and Development, NewYork, 1989.
Laksono Trisnantoro, ”Reposisi Dinas Kesehatan Akibat Kebijakan Desentralisasi dan Sistem Kesehatan Wilayah”,
dalam Laksono Trisnantoro (eds), Desentralisasi Kesehatan di Indonesia
dan Perubahan Fungsi Pemerintah 2001-2003: Apakah Merupakan Periode Ujicoba?, Gama Press, Yogyakarta,
2005.