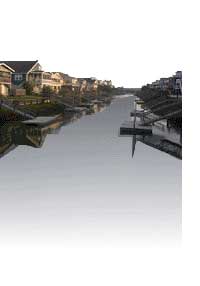|
Melacak Peran-Peran LSM
Dalam Proses
Kebijakan Publik
Oleh
Ashari Cahyo Edi
”Menurut sudut pandang rakyat miskin
di berbagai belahan dunia, krisis sedang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Walaupun ada begitu banyak institusi
yang berperan penting dalam kehidupan rakyat miskin, namun mereka tetap tersisih dari peluang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Lembaga-lembaga negara, entah itu yang diwakili kementerian-kementerian di tingkat pusat ataupun pemerintah-pemerintah daerah,
sering kali tidak akuntabel terhadap rakyat miskin; lebih dari itu...terdapat arogansi dan penghinaan yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga negara terhadap rakyat miskin. Celakanya, rakyat miskin tak menemukan jalan lain kecuali menjadi korban ketidakadilan,
kriminalitas, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi yang dilakukan oleh institusi-institusi negara, meskipun mereka ingin
bermitra dengan lembaga-lembaga itu berdasarkan aturan-aturan main yang lebih adil.”
Menjaga Kepentingan Publik Dalam
Proses Kebijakan
Kepengurusan sektor
publik dan bidang-bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama secara intensif kian bergeser ke arah pendekatan inklusif
dan melibatkan banyak pihak yang terkait (multistakeholders). Dalil bahwa sektor publik dan kepengurusannya semata
kewenangan agensi negara—urusan internal pemerintah dan bagian dari rutinitas birokrasi—kini tengah digugat. Ini
sejalan dengan ide bahwa penyelenggaraan pemerintahan tak lagi dipahami sebagai penggunaan otoritas negara secara legitimate,
namun juga sebagai interaksi antara pihak-pihak terkait untuk menghasilkan capaian optimal.
Tata kelola pemerintahan
juga bukan semata proses penggunaan otoritas negara terhadap rakyat tapi juga penggunaan hak-hak rakyat di hadapan negara. Pendekatan lama yang tertutup dengan hanya pemerintah sebagai aktor dominan, dinilai oleh aktor-aktor di luar negara
(masyarakat sipil dan sektor swasta) menjadi biang malapraktik administrasi, kebijakan yang tidak aspiratif, serta
sistem yang rentan dibajak oleh rent seekers atau aparat penjual rente.
Perubahan pendekatan
ini tidak saja terjadi di aras nasional, namun juga tengah melanda aras pemerintahan lokal. Pendekatan government yang
mengutamakan hierarkhi otoritas, di mana negara sebagai pihak omnipotent (mahakuat), kini tengah bergeser ke arah pendekatan
governance. Filosofi dasar dari governance mencakup nilai kesetaraan, kooperasi, akomodasi, toleransi, serta
pembentukan konsensus di antara sektor negara, privat dan masyarakat sipil. Filosofi ini melandasi pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengatur urusan-urusan negara, yang
memiliki mekanisme, proses, hubungan, serta kelembagaan yang kompleks di antara ketiga pihak tersebut (UNDP, 1997).
Di aras internasional,
konsep governance naik daun terkait dengan promosi dan pengharusan negara-negara terutama belahan Selatan untuk mengadopsi
resep pembangunan di bawah ”rubrik” program good governance. Konsep ini diintrodusir akibat kekecewaan
atas kegagalan berbagai skema pembangunan karena korupsi dan praktik-praktik menyimpang lainnya. Sedangkan dalam konteks domestik,
munculnya governance didorong oleh ingatan dan pengalaman historis kolektif betapa peran negara yang sedemikian intervensionis
(di negara demokratis) dan menindas (di negara otoriter) telah menyengsarakan kehidupan rakyat.
Hakikatnya, konsep
kemitraan negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam governance adalah
untuk menciptakan checks and balances of power, memberi batasan-batasan bagi lingkup otoritas negara dan pasar. Konsep
ini diidealkan berlaku nyaris di hampir semua bidang kehidupan yang kompleks, di mana berbagai kepentingan saling berkontestasi.
Dari sini, pendekatan governance kian mengemuka sementara konsep government makin kehilangan daya pikat dan
pengaruh.
Meski masing-masing
aktor (element) dari governance ini memiliki peran dan mandat sendiri-sendiri, namun kepengurusan urusan bersama
terutama pembahasan mengenai regulasi yang menyangkut peran masing-masing aktor ini setidaknya menjadi salah satu simpul persinggungan
di antara ketiganya. Terlebih jika itu berhubungan dengan sektor-sektor strategis, yang potensial menentukan dan menyangkut
irisan kepentingan ketiganya.
Terkait dengan kepengurusan
kepentingan bersama tersebut, dalam hal ini sektor publik—yang menyangkut hajat hidup orang banyak—advokasi kebijakan
yang diusung oleh civil society menjadi krusial. Di dalam kondisi transisi—di mana perubahan melalui reformasi
lebih bercorak ”inkremental”-gradual, diwarnai tarik-menarik pembaharu dengan status quo—mengharuskan
civil society mengadvokasi diri berikut kepentingan elemen-elemennya. Terutama elemen civil society yang berbentuk
civil society organization aktif mengorganisir, menyebarkan counter wacana, dan berupaya memperjuangkan hak-hak
warga negara di dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka.
Terlebih lagi iklim
sosial dan politik Indonesia kekinian memang lebih terbuka, beragam, dan mulai beranjak menuju tata kelola yang menyertakan
peran serta sektor pasar dan masyarakat. Oleh masyarakat sipil, perubahan pendekatan ke arah governance ini berusaha
dimanfaatkan untuk memperjuangkan terpenuhinya civil rights, political rights, dan social rights warga negara. Sebab, liberalisasi politik, reformasi, dan desentraliasi selama ini belum mampu mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok
miskin-marjinal baik secara sosial, ekonomi maupun politik.
Kenyataannya, sementara
ini demokrasi lebih banyak dimaknai dan diejawantahkan secara prosedural dan superficial sesuai kehendak pemerintah.
Sehingga dampak yang terasa lebih banyak berupa penggunaan istilah-istilah seperti partisipasi, gender budget, sampai
good governance di kalangan pemerintah atau lebih khusus lagi birokrasi. Pemenuhan hak-hak civil, sosial, dan
politik warga negara, peningkatan kualitas hidup, serta pelayanan publik masih jauh dari harapan. Dengan nada satir,
kutipan dari Narayan dkk (2000) di awal bagian pendahuluan ini melukiskan keterpurukan masyarakat miskin dan marjinal di hadapan
lembaga-lembaga pemerintah yang tak mampu memenuhi kewajiban asalinya. Walau begitu, sebenarnya masyarakat miskin dan marjinal
tersebut masih punya keinginan untuk bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintah di bawah aturan main yang lebih fair.
Advokasi kebijakan
atas kepentingan publik bergerak dalam kerangka tersebut. Advokasi kebijakan berupaya menciptakan arena dan saluran keterlibatan
publik dalam kebijakan jika itu tidak ada; membuat arena dan saluran partisipasi bekerja jika telah ada; lalu mendorong dan
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga negara untuk mengisi arena dan saluran partisipasi dan deliberasi untuk mempengaruhi
proses pembuatan keputusan yang menentukan nasib orang banyak. Tanpa upaya ini, selain tak terjaminnya pemenuhan hak-hak tadi,
di iklim post-otoritarianism sisa-sisa kekuatan dan kepentingan status quo berpotensi akan membajak sistem baru
yang lebih demokratis ini untuk mempertahankan status quo.
Salah satu sektor
yang menyangkut hajat hidup publik yang diadvokasi adalah kesehatan. Sektor ini bersanding dengan isu pendidikan dan kesejahteraan
sosial secara umum, termasuk juga penanggulangan kemiskinan. Sebagai hak, selama ini pelayanan kesehatan bagi kebanyakan orang
miskin dan paling miskin di negeri ini adalah sesuatu yang mahal. Sayangnya, pembuatan kebijakan di bidang kesehatan terutama yang terkait dengan pelayanan, belum memberi ruang bagi partisipasi dan lebih-lebih deliberasi publik. Sebagai pihak
yang akan terkena imbas langsung dari kebijakan, dan lebih mendasar lagi sebagai pihak yang telah memilih dan mempercayakan
kedaulatannya kepada pemerintah, publik justru termarjinalkan secara politik.
Bukan rahasia lagi
jika pemerintah mengutamakan keterlibatan publik hanya dalam fase implementasasi kebijakan. Itupun sekadar partisipan pasif.
Padahal, proses formulasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan. Di sana tak hanya terjadi proses-proses teknikalitas
namun juga melibatkan dimensi politis terkait dengan pemilihan opsi pemecahan persoalan yang akan diangkat dalam kebijakan—yang
berarti memutuskan pihak mana mendapat manfaat atas beban pihak yang lain. Kalaupun warga dilibatkan, bentuknya sebatas konsultasi
satu arah. Publik tak bisa menolak dan paling maksimal hanya menambal sulam bagian-bagian tertentu.
Hari-hari ini banyak pemerintah daerah sedang dan telah memberlakukan berbagai peraturan daerah yang intinya
menaikkan sumbangan publik dalam pelayanan publik sebagai jalan keluar masalah. Sektor kesehatan, salah satunya. Minimnya
pendanaan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecilnya pos anggaran publik di APBD, berikut rendahnya
inovasi kebijakan daerah untuk menyiasati keterbatasan anggaran, mendorong banyak daerah untuk meningkatkan retribusi masyarakat
dalam pelayanan kesehatan. Kebijakan pengetatan penjaminan kesehatan publik melalui anggaran oleh negara juga terkait dengan
kebijakan penyesuaian struktural yang didorong oleh IMF dan World Bank sebagai resep paket reformasi ekonomi yang menekankan
efisiensi.
Beranjak dari setting
makro tersebut, kecenderungan pemda untuk membuat regulasi (perda) yang berkehendak untuk menaikkan tarif puskesmas/rumah
sakit yang melibatkan kerja teknokrasi—studi formulasi penghitungan tarif baru puskesmas, di mana pemda ingin menerapkan
tarif pelayanan puskesmas yang rasional-ekonomis sehingga bea pelayanan tidak melulu membebani anggaran daerah; dan itu berarti,
porsi sumbangan masyarakat dalam sharing pembiayaan menjadi bertambah—memerlukan peran elemen masyarakat sipil
melalui advokasi kebijakan.
LSM harus aktif melakukan
advokasi kebijakan. Selain menuntut perubahan substansi raperda, dalam hal ini mengerem kenaikan harga layanan agar affordable
sembari mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan mestinya dijamin penuh oleh negara, LSM dituntut aktif membuka ruang bagi terali
besi agar ada ruang bagi partisipasi dan pengaruh bagi publik. Rangkaian proses FGD di komunitas, polling, lobi parlemen,
hearing dengan pemda dan metode advokasi lain ini ditujukan guna menumbuhkan kesadaran warga akan hak-hak warga negara,
mendorong adanya ruang partisipasi, mendesakkan pengaruh baik ke eksekutif, legislatif, dan opini publik.
Efektivitas LSM dalam Advokasi Kebijakan
Advokasi adalah upaya
untuk menegakkan suatu keseimbangan kekuasaan yang tepat antara warga negara dengan lembaga-lembaga pemerintah: ”Advocacy
is about influencing or changing relationships of power,” (World Bank-CSI, 2001). Aktivitas Advokasi adalah proses di mana individu-individu dan organisasi berusaha mempengaruhi keputusan kebijakan
publik. “At
its best, advocacy expresses the power of an individual, constituency, or organization to shape public agendas and change
public policies,” (USAID-Office of Democracy and Governance, 2001). Dari definisi di atas tampak bahwa relasi kekuasaan yang seimbang antara negara dan masyarakat dikerangkai oleh hadirnya
kebijakan baru yang merevisi kebijakan lama.
Aktivitas advokasi
selalu akan memulai dengan motif kecurigaan terhadap kekuasaan. Di manapun dan dalam hal apapun, kekuasaan tetap merupakan
kekuasaan, “(which) tends to corrupt, and absolute power corrupts abolutely,” demikian kata Lord Acton.
Kecurigaan advokasi berpihak pada warga yang miskin, tak punya afiliasi politik, berpendidikan rendah, sehingga tak mampu
mempengaruhi dan mengontrol proses-proses politik yang berdampak pada kehidupan mereka. Warga ini tak berdaya dan marjinal
bukan karena takdir melainkan akibat sistem, struktur, dan lingkungan yang hirarkhis, menindas, tidak memberdayakan.
Sudah barang tentu,
aktivitas advokasi yang berlawanan arus dari kebijakan pemerintah maupun suara arus utama (mainstream) akan memunculkan
ruang perdebatan: ada gugatan balik dan penguatan klaim. Sebagai proses, hal ini sejatinya adalah bagian dari keberhasilan
advokasi yang paling dini, sebab berhasil mengajak pemerintah dan publik untuk mengamati, menimbang suatu persoalan, mendesiminasikan
perspektif alternatif baik itu di forum-forum diskusi publik seperti hearing dengan pemerintah maupun legislatif, debat
opini media, serial pemberitaan di surat kabar, dan sebagainya. Setiap orang akhirnya menjadi tahu duduk soal sebenarnya.
Karena itu, advokasi
bukanlah revolusi yang membongkar dan menjungkirkan rezim. Advokasi adalah upaya koreksi atas ketidaktepatan visi kinerja kekuasaan (kebijakan) dari suatu institusi yang mengemban
otoritas yang sah dalam suatu sistem. Yang dikalukan lebih pada bagaimana mendalamkan proses-proses demokrasi yang ada dan
memperkuat berbagai lembaga demokrasi agar bekerja melebihi capaian prosedural. Tujuan akhir advokasi adalah membuat relasi
masyarakat dan negara menjadi lebih demokratis. Dampak politik yang harus diraih oleh para aktivis adalah terjadinya perubahan
relasi kekuasaan yang mengarah pada makin menguatnya daya tawar politik rakyat.
Advokasi kebijakan merupakan pilihan yang logis dan kontekstual dari perubahan konteks politik sebagaimana dijelaskan
di depan. Advokasi kebijakan menandai suatu pergeseran di dalam gerakan NGO dari kontestasi dan vis avis menjadi partnership
dalam arti critical engagement. Jika dulu berpartisipasi dalam proses kebijakan diemohi karena didominasi birokrasi
dan watak otoriter negara, kini warga bisa meminta audiensi, hearing, mempengaruhi, kendati dipenuhi berbagai keterbatasan.
Dulu, ekstrimnya, mengorganisir masyarakat, memaksimalkan potensi kemandirian karena kebijakan negara nyaris sulit dipengaruhi.
Pendekatan advokasi mengarah pada bentuk-bentuk pengorganisiran, menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, di mana masyarakat
“sekadar” menekan policy makers. Sementara advokasi kebijakan dalam konteks baru ini lebih bersinonim dengan—dalam
istilah Gaventa, co-governance—keaktifan warga untuk menjadi mitra pemerinta,
terlibat aktif, mengawal, menjadi partner kritis, dalam proses-proses kebijakan.
Veneklasen dan Miller mengingatkan bahwa advokasi kebijakan kerap terjerumus dalam pertarungan yang sia-sia. Kegagalan memperhitungkan
costs and benefits bisa menjerumuskan sumber daya CSO ke dalam proses yang panjang, melelahkan, sementara ketika dimenangkan,
suatu kebijakan belum tentu dilaksanakan secara konsekuen. Karena itu, advokasi kebijakan perlu dibarengi dengan upaya edukasi
terhadap warga negara agar kemenangan di ranah kebijakan bisa dijaga, dikontrol impelmentasinya, dan berlanjut.
Kemenangan dalam arti perubahan kebijakan atau disahkannya kerangka legal yang melindungi hak-hak publik tidak selalu
memberi keuntungan sesaat. Misalnya, jaminan partisipasi, trasparansi, dan akuntabilitas melalui regulasi, tidak saja berdampak
pada praktik pemerintahan dan kebijakan yang baik, namun dalam jangka panjang menjanjikan ruang bagi inisiatif dan terobosan
untuk pendalaman demokrasi dengan implikasi pada tercapainya pengurangan kemiskinan, pelayanan publik yang adil, dan sebagainya.
Dalam praktiknya, setidaknya, aspek legitimasi maupun kredibilitas memegang peran penting bagi afektivitas advokasi
kebijakan oleh LSM. Pemerintah, kerap tak mempedulikan substansi advokasi, mempertanyakan legitimasi ataupun kredibilitas
sebuah LSM. Karena itu, , CSO harus mengupayakan terpenuhinya setidaknya untuk dua aspek ini. “Legitimasi merujuk pada
siapa yang diwakili oleh organisasi itu dan hubungannya dengan mereka... Siapa berbicara untuk siapa dan dengan otoritas apa?”
Sedangkan aspek kredibilitas merujuk “seberapa jauh sebuah organisasi dipercayai, mislanya kualitas informasinya, programnya,
layanannya.” Suatu CSO dikatakan tidak punya kredibilitas, misalnya, mengaku menghasilkan rekomendasi kebijakan melalui
polling padahal sebenarnya tidak.
Efektivitas advokasi
juga bergantung pada pendekatan dan strategi terhadap kekuasaan yang riil. Gaventa memberikan rumusan mengenai karakter kekuasaan yang tengah bekerja. Karakter kekuasaan tersebut menjadi konteks bagi alternatif
strategi advokasi. Rumusan Gaventa ini menurut penulis melampaui diskusi pilihan
level advokasi kebijakan versus pengorganisiran akar rumput.
Pada karakter kekuasaan
pertama, demikian Gaventa, kekuasaan dipahami sebagai hasil dari pertarungan kelompok-kelompok kepentingan. Ada pihak
yang kalah dan ada pihak yang menang. Dalam situasi tersebut, berbagai masalah kunci di masyarakat sudah disadari semua warga
negara. Semua proses politik hidup dalam sistem politik yang bersifat terbuka dan adil. Karena itu, orang yang tak berdaya
dan tak berpartisipasi terutama dikarenakan pilihan pribadi dengan menganggap suatu isu tidak serius. Bisa pula, tak
aktif dalam politik adalah ekspresi dari rasa puas atas status quo atau sebaliknya cerminan rasa apatis baik karena
tidak yakin mampu mempengaruhi proses politik maupun tiadanya sumber-sumber ekonomi untuk bersaing secara efektif dalam proses
politik.
Strategi advokasi dan pemberdayaan untuk karakter kekuasaan pertama ini disebut advokasi kepentingan
umum. Fokusnya adalah memberi bantuan artikulasi suatu kepentingan dan membuat kepentingan tersebut diutamakan
dalam perumusan kebijakan publik. Strategi kepentingan umum membangun efektifitas politik dan ketrampilan advokasi
yang diperlukan mempengaruhi kebijakan. Strategi ini umumnya memilih isu sempit yang mudah dimenangkan dalam kerangka aturan
main sistem yang berlaku. Cara yang dipilih yakni menyusun agenda, formulasi, penegakan, dan atau mencabut kebijakan/UU. Dalam
strategi ini, advokasi dipimpin para pakar dan profesional. Rakyat diadvokasi oleh para pembela kepentingan publik atau “advokasi
bagi rakyat”, yang bicara atas nama warga negara. Merekalah yang melobi elit, memobilisir kelompok untuk mendukung cita-cita,
dan melatih orang dalam ketrampilan tertentu yang terkait dengan kampanye, seperti menyurati politisi.
Selanjutnya tipologi
kekuasaan kedua, yang memahami kekuasaan sebagai hasil dari keputusan satu atau sejumlah kelompok-kelompok masyarakat
yang duduk di meja. Mereka menentukan mana masalah/keluhan yang akan dikenali, diutamakan, dengan mendiskriminasi kepentingan
kelompok masyarakat tertentu. Di sini, bagi Gaventa, sistem yang terbuka bukan segalanya. Ketakberdayaan dan tiadanya partisipasi,
karena itu, disebabkan oleh hambatan sistemik atau struktural yang menjaga agar kelompok tertentu dan masalah tertentu jangan
sampai ke meja pembuatan kebijakan. Ketakberdayaan juga muncul dari tak berimbangnya kekuasaan, saat proses-proses politik
tidak terjangkau, serta sistem politik mencegah populasi tertentu ikut dalam politik—kebijakan. Strategi advokasi dan
pemberdayaannya adalah “advokasi dengan dan oleh rakyat”. Cirinya, ada organisator profesional baik individu
maupun lembaga yang membangun kepemimpinan setempat. Orientasi advokasi pada masalah penting di komunitas yang “dapat
dimenangkan”, menarik akar rumput, dan menantang struktur-strtuktur; membangun organisasi akar rumput yang kuat untuk
mendapatkan kekuasaan dan akses dan membawa masalah-masalah kebijakan ke meja untuk ditindaklajuti dan ditegakkan.
Pada tipologi kekuasaan
yang ketiga, Gaventa menguraikan bahwa kekuasaan adalah hasil dari upaya negara mencegah timbulnya konflik kepentingan,
ideologis, terkait dengan penciptaan stabilitas. Untuk itu, para pemegang kekuasaan membentuk kesadaran dan kewaspadaan tentang
berbagai masalah melalui proses sosialisasi, pengendalian informasi, yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi. Menurut
Gaventa, warga menjadi tidak berdaya dan terlempar dari proses partisipasi karena tidak memiliki kesadaran kritis, akibat
penindasan nilai yang diinternalisasikan paksa, yang dari sana menguatnya hegemoni hingga rakyat akhirnya mempermasalahkan
diri.
Untuk menghadapi tipologi kekuasaan ini, maka strategi advokasi dan pemberdayaannya dilakukan melalui “advokasi
oleh rakyat”. Strategi ini ditandai dengan kepemimpinan advokasi berada di akar rumput. Pendidikan menjadi penting
dalam mengembangkan kesadaran politik, kepercayaan, makna hak, dan untuk mengidentifikasi masalah mendesak yang menantang
struktur. Advokasi juga memperkuat kekuasaan dan pertanggungjawaban kelompok, pengetahuan setempat, dan memantau implementasi
kebijakan dan penegakan kebijakan. Pendekatan transformasional mengakui pentingnya pendekatan melobi dan mengorganisasi.
Hal lain yang perlu diperhatikan agar advokasi kebijakan LSM efektif, adalah adanya mindset bahwa advokasi
kebijakan tak sekadar merupakan kerja-kerja politik namun juga kerja-kerja teknokratik. Jika kerja politik menonjolkan upaya-upaya
menyeimbangkan kekuasaan, lobi-lobi, mempengaruhi opini publik, dst., maka kerja teknokratik melibatkan kapasitas CSO dalam
memahami secara kritis proses kebijakan, melakukan observasi dan analisis, guna menyusun argumentasi dan merumuskan solusi-solusi
praktis. Ini penting agar rumusan substansi normatif bisa masuk dalam substansi kebijakan hingga teknis implementasi. Sebab,
merujuk laporan Overseas Development Institute, bahwa gagasan, solusi, atau rekomendasi dari CSO kerap diragukan oleh pengambil kebijakan maupun kalangan ahli/peneliti
kebijakan publik. Bagi pembuat kebijakan, kajian, argumentasi, rekomendasi CSO meragukan dari aspek daya practicability;
sementara bagi peneliti maupun analis kebijakan kajian, argumentasi, dan rekomendasi CSO meragukan dari aspek validitasnya.
Advokasi kebijakan juga lebih efektif ketika ia berjalan di dua lini. Masyarakat/CSO dan
negara. Membangun kesadaran, nilai, pengetahuan, dan ketrampilan di level masyarakat. Ini merupakan strategi edukasi. Sementara
di level negara, dengan strategi persuasi mendorongnya agar responsif terhadap aspirasi masyarakat. Karena logika policy
advocacy dalam konteks demokratisiasi, maka berbagai input perlu dikomunikasikan secara tepat. Anti-politics legacy
dari Orde Baru masih melekat pada diri birokrasi dan lembaga pemerintah lainnya. Mereka enggan bahkan takut membuka diri
terhadap kritik dan masukkan sehingga komunikasi dalam pembuatan maupun evaluasi kebijakan tidak berjalan. Persoalan SDM,
keterbatasan inovasi, aksi yang lambat juga turut disebabkan oleh problem regulasi, kultur, sehingga sekadar kritik LSM tanpa input rekomendasi yang konkret acap membuat pemerintah menjadi kian eksklusif.
Ruang Advokasi dalam Proses Kebijakan
Pada kenyataannya,
kebijakan bukan hanya satu keputusan melainkan serial keputusan dan non keputusan, di mana keputusan itu sendiri tak lain
adalah kekuasaan (power). Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah segala segala keputusan pemerintah baik keputusan
untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu (not to act, the non decision). Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan adalah a purposive behaviour, suatu perilaku tindakan yang mempunyai maksud.
Maksud ini kerap berbeda dari statemen yang secara resmi diumumkan oleh pemerintah. Visi dan misi sesungguhnya tersembunyi.
Dan tak jarang, demikian Turner & Hulme (1997: 58), rasionalisasi mengenai inisiatif dan dampak dari kebijakan malah dimunculkan
belakangan setelah keputusan dibuat dan tindakan dilakukan.
Dalam logika demokrasi,
kebijakan publik adalah wujud konkret dari “kontrak” negara dengan rakyat mengenai apa-apa yang akan dilakukan
untuk mencapai kepentingan bersama—seperti yang diikonkan oleh filusuf Perancis JJ Rousseau sebagai the social contract
or principles of political rights. Atas nama menjaga kontrak tersebut, maka intervensi dilakukan melalui advokasi dengan tujuan memperdalam substansi maupun
melengkapi proses formal-prosedural agar apapun pendekatan yang dipilih pemerintah tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
Terutama, kelompok yang akan terimbas langsung.
Penulis merasa tidak
pada tempatnya membahas berbagai pendekatan yang ada dalam pembuatan kebijakan. Penulis menganggap penting dua pendekatan
yakni birokrasi (kelembagaan) dan teknokrasi, di mana keduanya umum digunakan pemerintah. Pendekatan birokrasi melihat struktur negara sebagai arena di mana ofisial publik
terlibat dalam manuver-manuver politik untuk mengamankan “dampak-dampak politis”. Birokrasi membangun koalisi,
penawaran, kompromi, kooptasi, menjaga informasi, dan membuat strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya.
Tujuannya adalah mengontrol area kebijakan dengan fokus tertentu di mana aktor-aktor terlibat.
Model birokratik mengidentifikasi
organisasi dari negara sebagai yang dikacaukan dalam konflik politik yang konstan untuk menentukan opsi kebijakan mana yang
dipilih dan bagaimana mereka dilaksanakan. Pendekatan birokrasi umumnya melibatkan pendekatan teknokrasi dalam membuat suatu
kebijakan. Pendekatan ini mengatakan bahwa suatu masalah harus diselesaikan oleh pihak yang memiliki legitimasi keahlian
(expertise) tertentu. Keahlian tersebut mencakup kapasitas mendekati persoalan berdasarkan metode ilmiah dan karena itu
diklaim objektif dan tidak berpihak.
Pemerintah memperkuat
basis argumennya dengan menggunakan jasa expertise dan analis profesional kebijakan baik sebagai think tank tetap
maupun advisory by project untuk membuat draf akademik rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan daerah.
Ini dilakukan untuk menguatkan dan mempengaruhi opini publik bahwa pilihan kebijakan dalam, sejak dalam formulasinya, telah
sedemikian bebas kepentingan dan ilmiah.
Berbagai temuan para
analis kebijakan (arus utama) tersebut ditempatkan sebagai segalanya karena sejalan dengan kepentingan pemerintah. Atas nama
netralitas keilmuan, hasil kerja para ahli ini jarang sekali bisa digagalkan untuk menjadi dasar dari sebuah regulasi. Alhasil,
pembacaan terhadap kebutuhan dan aspirasi cukup dengan suatu penelitian, bukannya melalui proses policy making yang
terbuka, partisipatif, dan deliberatif. Seringkali politisi dan birokrasi, dengan berbasis kajian akademik, merasa lebih tahu
tentang apa yang diinginkan rakyat dengan menganggap bahwa rakyat tidak punya rasionalitas nilai, tak punya apa-apa, bahkan
tentang kebutuhannya sendiri. “There is a lack of capacity building for technical and scientific personnel to foster those participatory
skills, attitudes and behaviour which are needed to learn from citizens (mutual listening, respect, gender sensitivity as
well as methods for participatory learning and action,” tegas Pimbert. Kesehatan, tata ruang dan wilayah, bio genetik, infrastruktur adalah sejumlah bidang yang melibatkan teknokrasi dan peran
expertise di dalam perumusan kebijakannya. Alhasil, kebijakan menjadi satu arah dan top down.
Dalam bidang kesehatan misalnya, sebagaimana temuan Laporan Tahun Ketiga, Indonesia Rapid Decentralization
Appraisal (IRDA), hal itu disebabkan karena dengan begitu maka proses pengambilan keputusan menjadi cepat dan efisien. Proses seperti
itu juga membantu menyelaraskan antara (teknokrasi) perencanan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terakhir, (teknokrasi)
pemerintah daerah lebih memadai untuk memahami kebutuhan daerah.
Ketika kebijakan hanya
bergulir sebagai rutinitas internal pemerintah ada sejumlah konsekuensi. Secara filosofis, terjadi keterputusan dimensi epistemologi
antara pemerintah dengan masyarakat akibat teknokrasi yang menganulir partisipasi. Kasus umum, saat pemerintah menyosialisasikan
kebijakan yang sudah siap diimplementasikan, ternyata masyarakat melihat output tersebut masih sebagai sebuah rancangan
kebijakan yang butuh diperdebatkan.
Kebuntuan saluran
partisipasi ‘formal’ pada gilirannnya juga acap memunculkan aksi-aksi jalanan sebagai instrumen alternatif dalam
menyuarakan aspirasi yang dinilai tidak berbelit-belit dan tidak terjebak dalam prosedur birokrasi. Pendekatan kebijakan di
atas menyebakan keterlibatan publik dalam kebijakan menjadi kaku, prosedural, rumit, dan tidak bersahabat bagi warga miskin.
Partisipasi hanya difungsikan sebagai mobilisasi dan proses mendukung pemerintah, sosialisasi kebijakan, sebatas menjatuhkan
pilihan (vote), bukannya sebagai substansi (voice); dalam titik ekstrim, hal ini memunculkan tirani partisipasi
yang menimbulkan distrust warga negara (dan state denial) terhadap pemerintah.
Karenanya,
peran baru yang harusnya diemban oleh birokrasi dan ahli/profesional. Kata Pimbert, “(The) existing bureaucracies and professionals
will often need to shift from being project implementers and deliverers of standard services and technologies to new roles
that facilitate local people’s analysis, deliberations, planning, action, monitoring and evaluation.” Intervensi
bisa dilakukan di setiap tahapan pembuatan kebijakan. Baik di fase agenda setting, formulation, decisioning, pelaksanaan
maupun evaluasi pelaksanaan. Berikut ini tahapan kebijakan dann tujuan yang diharapkan dari intervensi.
“Agenda setting: Awareness of and priority given to an issue
or problem.
Policy formulation: How (analytical and political) options and
strategies are constructed.
Decision making: The ways decisions are made about alternatives.
Policy implementation: The forms and nature of policy administration
and activities on the ground.
Policy evaluation: The nature of monitoring and evaluation of
policy need, design, implementation and impact.”
Fase-fase
kebijakan ini potensial untuk dimanfaatkan NGO menjadi saluran melakukan intervensi. Dalam agenda setting misalnya,
terjadi proses di mana suatu isu—di antara berbagai isu yang ada—diupayakan menjadi perhatian untuk diangkat sebagai
masalah kebijakan atau kesempatan untuk diambil tindakan sebagai kebijakan. “Agenda seeting is deciding whether a
new policy or policy reform is required in the first place.” Intervensi pada fase ini adalah agar suatu isu advokasi bisa masuk ke dalam agenda politik untuk didiskusikan dan
diaksikan.
Sementara dalam tahap formulasi
kebijakan di bahas, “...details such as a statement of the problem, the goals and objectives of the policy, a framework
that sketches programs in support of the targets, and a statement of the resources needed for this policy are sketched and
analyzed in elaborate detail so that effective action and implementation can be carried out (Burke, 1990; Starling, 1988). Fase formulasi kebijakan merupakan ruang di mana CSO bisa menawarkan rumusan alternatif kebijakan.
Sedangkan intervensi dalam pembuatan keputusan (decision making)
pada bagaimana mempengaruhi proses di mana suatu kebijakan diputuskan yang dalam hal ini berlangsung di parlemen dan secara
prosedur melibatkan eksekutif dan legislatif. Karena posisi masyarakat sebatas dikonsultasikan, maka CSO berkepentingan untuk
mengawal, mengetahui substansi yang berubah, dan terus-menerus melakukan intervensi.
Pemanfaatan Ruang Advokasi oleh LSM
Seperti disinggung
sebelumnya, pemahaman bahwa advokasi kebijakan sekadar kerja politik selama ini turut menjadi faktor tak efektifnya input
dari NGO dalam proses kebijakan. Yang kerap terjadi, NGOs lebih bermain di ranah normatif, hanya merujuk landasan legal, tanpa
diperkuat kajian, argumentasi, dan rekomendasi yang dapat diterapkan. Argumentasi yang bersifat normatif tersebut juga
kadang digunakan untuk tahapan proses pembuatan kebijakan di mana pembahasannya telah menginjak aspek-aspek praktis, strategis,
yang melibatkan konsekuensi biaya dan manfaat. Karena itu, agar efektif dalam memanfaatkan peluang advokasi dalam proses kebijakan,
NGO dituntut mampu memahami proses kebijakan, mengobservasi konteks, menyiapkan substansi yang tepat untuk mempengaruhi tiap
proses tiap fase pembuatan kebijakan.
Court, Mendizabal,
Osborne (ODI, 2007: 32) menjelaskan, misalnya dalam agenda setting, NGO diharapkan mampu meyakinkan pengambil kebijakan bahwa suatu isu sungguh
memerlukan perhatian. Pada fase ini NGO dituntut memiliki penguasaan terhadap evidence untuk mempercanggih kredibilitas
argumennya. NGO juga perlu memperluas kampanye advokasi kebijakan, mengembangkan jalinan antara aktivis NGO dengan para peneliti
kebijakan, dan pemangku kebijakan. Proses agenda setting memerlukan input evidence dari NGO berupa policy
naratives, suatu kajian yang kredibel, sesuai dengan lingkungan politik, yang kemudian dikomunikasikan secara efektif.
Dalam fase formulasi,
kajian, argumentasi, dan rekomendasi NGO tak sebatas seruan normatif melainkan sudah menukik ke hal-hal yang bersifat praksis.
Dalam hal ini, NGO memberikan pengaruh melalui input berupa informasi tentang pilihan-pilihan kebijakan. Ringkasnya, NGO menjadi
sumber substansi yang menyalurkan keahlian ke dalam proses kebijakan. Misalnya, dalam suatu advokasi penganggaran (budgeting),
ketika mengidentifikasi potensi inefisiensi dalam RAPBD, maka ia pun harus memberi saran realokasi, argumentasi program alternatif
berikut gambaran detail kegiatan, agar meyakinkan pengambil kebijakan.
Dalam
fase implementasi, advokasi NGO ditujukan untuk mem-back up dengan melengkapi peran pemerintah. NGO bisa membantu dengan
mem-back up kapasitas pemerintah dalam hal pencapaian dan keberlanjutan kebijakan,
melakukan inovasi penyelenggaraan pelayanan (service delivery), membuat pelayanan menjangkau kelompok marjinal.
Dalam tahapan ini, NGO memberikan input yang bersifat lintas konsteks (generalisable across different contexts), operasional
(how to do it), yang semuanya itu dikomunikasikan secara langsung kepada pembuat kebijakan.
Dalam evaluasi kebijakan,
intervensi NGO ditujukan untuk melakukan reviu atas pengalaman praksis pelaksanaan kebijakan. Hasilnya, dalam bentuk pelajaran dan catatan kritis, dimasukkan ke proses pembuatan kebijakan selanjutnya. NGO bisa
membantu menghubungkan pembuat kebijakan dengan pengguna atau penerima manfaat atau dampak kebijakan. NGO memberikan feedback
yang berkualitas dan representatif. Pada tahap ini, input NGO atau LSM dalam bentuk rekomendasi, pengetahuan, dst., harus
konsisten untuk keperluan monitoring; obyektif; seksama, dan relevan; dikomunikasikan dengan cara yang jelas.
Democratic
Expertise?
Ke depan,
peran masyarakat dan LSM dalam kebijakan dibutuhkan agar kebijakan berpihak kepada publik. Pengetahuan tak boleh dimonopoli
sebab pengetahuan dari pihak tertentu (think tank pemerintah) atau mainstream perspektif
tertentu sejatinya serba terbatas. Baik karena persoalan kehidupan begitu kompleks maupun resiko dari formula solusi dari
pihak/perspektif tertentu yang boleh jadi membawa resiko yang tak terprediksi oleh formula itu sendiri. Kontestasi secara
terbuka dan fair antar ide menjadi keharusan.
LSM
dan masyarakat, dalam konteks politik yang semakin plural—betatapun di sana-sini terdapat lubang-lubang—hendaknya
juga semakin aktif urun rembug dalam kebijakan. Jika expertise, think tank, konsultan dulu lebih banyak didominasi pihak pemerintah dan aliran utama sehingga cenderung
jadi oligarkhis, maka peran LSM dan masyarakat bisa menjadi penggerak dari apa yang saya pikir sebagai ”democratic expertise”. LSM bisa mengembangkan berbagai metode dan inovasi agar metode riset yang rumit bisa mudah dipahami dan diterapkan warga
guna memformulasi maupun mengukur kinerja suatu kebijakan publik.
Sehingga,
kontrol masyarakat maupun LSM ke depan tak sekadar demonstrasi, sekadar menuntut, tanpa basis data dan analisis, di mana warga
dan LSM memosisikan di luar garis proses kebijakan.
Narayan, D.C. Chambers Korten, R., Shah,
MK & Petesch, P, Voices of The Poor: Crying Out for Change, D.C. World Bank, 2000, dalam John Gaventa, “Enam
Proposisi Menuju Tata Pemerintahan Daerah Partipatoris”, dalam Sugeng Bahagijo & Rusdi Tagaroa (eds), Orde partisipasi;
Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran, Jakarta, Perkumpulan Prakarsa, 2005.
Civil rights secara umum terkerangkai
sebagai kemerdekaan individu yang mencakup hak bebas berbicara, berorganisasi, berdemonstrasi, equality before the law,
memiliki properti; political rights mencakup hak mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam politik/kebijakan, memilih
dalam pemilu, di mana semua itu membutuhkan penegakaan kesetaran politik dan pemerintah yang demokratis; dan, yang terakhir
social rights di mana negara memberi jaminan status sosial minimum, standard pelayanan dan pemenuhan hidup, jaminan
kesehatan, yang semuanya sebagai hak bagi warga negara untuk dapat hidup sesuai dengan standard yang berlaku di masyarakat.
T.H. Marshall dalam Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction, 2nd Edition, NY, Palgrave,
1999. Hal. 211.
Eko Prasetyo, “Advokasi Kebijakan,
Jalan menuju Pembebasan”, dalam Imam Subkhan (eds), Siasat Gerakan Kota; Jalan untuk Masyarakat Baru, Yogyakarta,
LABDA, 2003.
Valerie Miller dan John Covey, ibid.,
hal. 174-191.
Riant
Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, & Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
Penjelasan
ini antara lain disarikan dari Grindle dan Thomas (1989) dalam Mark Turner dab David Hulme, Governance, Administration,
and Development; Making The State Work, Palgrave, NY, 1997. Hal. 64-69. Dikutip juga dari Quentin Beresford, Government,
Market, and Globalisation: Policy in Context, Questin Beresford, Allen & Unwin, NSW, 2000. Hal. 14-16 dan 35-38.
Fadillah
Putra, Devolusi Politik: Desentralisasi sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik
Negara dan Rakyat, Pustaka Pelajar, 1999.
Michel
Pimbert, “Reclaiming Our Right to Power: Some Conditions for Deliberative Democracy”, dalam Pimbert & Wakeford
(eds),PLA Note 40: Deliberative Democracy and Citizens Empowerment, London, IIED, 2001.
Anonim, “A Modul On Public
Administration Policy Formulation and Implementation”. Sumber <ttp://www.termpapergenie.com/Public Administration
Policy.html>. Tanggal download 2 Mei 2006.
Istilah ini saya pinjam dari E. J. Woodhouse & Dean Newsman, “Democratic
Expertise: Integrating Power, Knowledge, and Participation”, Rensselaer Polytechnic Institute. Papr ini diadaptasi penulisnya
dari E.J. Woodhouse and
Dean Nieusma, "When Expert Advice Works, and When it Does Not," IEEE Technology and Society Magazine, Spring 1997,
23-29. Sumber: http://www.rpi.edu/~woodhe/docs/HoppeDemExp.htm. Diambil medio Maret, 2006, pukul 16.00 WIB.
|